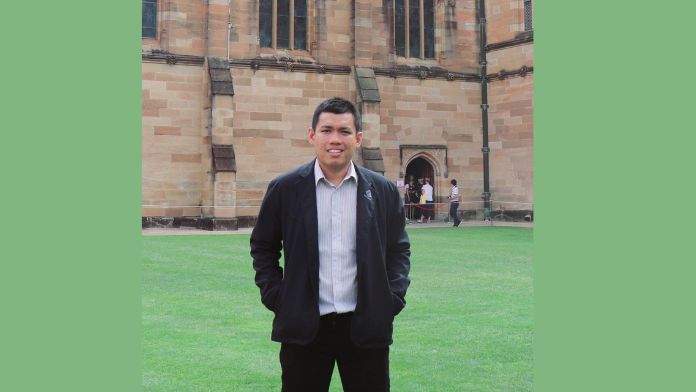Dekonstruksi Kesombongan Manusia: Refleksi Kritis Ekoteologi
Dekonstruksi Kesombongan Manusia: Refleksi Kritis Ekoteologi
Fadhlur Rahman
Dosen UIN SUNA -Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe.
Di tengah krisis ekologis global, muncul kesadaran bahwa kesombongan manusia dalam memperlakukan alam telah membawa dampak yang merusak bagi kehidupan. Refleksi kritis ekoteologi hadir untuk membongkar cara pandang manusia yang antroposentris, sekaligus mengajak pada sikap kerendahan hati dalam memperlakukan seluruh ciptaan. Oleh karena itu, tulisan ini berupaya menghadirkan sebuah refleksi kritis atas wacana ekoteologi, dengan menempatkan pembahasan secara khusus dalam konteks Indonesia kontemporer, terutama dalam menekankan pentingnya ekologi spiritual. Dengan berlandaskan arah kebijakan nasional ini, melalui Menteri Agama (Prof Nasaruddin Umar), artikel ini berargumen bahwa keterlibatan mendalam dengan ekoteologi bukanlah sekadar latihan intelektual, melainkan jalur krusial untuk memulihkan identitas manusia, sebagai makhluk, yang autentik dan rendah hati.
Semakin dalam seseorang menyelami refleksi ekoteologis, maka akan semakin tumbuh kesadaran akan kerendahan hati yang mendasar dalam pandangan tentang manusia. Manusia tidak lagi menempatkan dirinya sebagai pusat segala sesuatu, melainkan sebagai bagian dari ekosistem ciptaan Tuhan. Ekoteologi menunjukkan betapa eratnya hubungan timbal balik antara manusia dengan seluruh makhluk hidup. Dari sini lah muncul interpretasi pemahaman bahwa manusia memiliki tanggung jawab moral untuk merawat dan menjaga kelestarian seluruh ciptaan Tuhan.
Martin Heidegger, meskipun bukan seorang teolog, mampu menangkap esensi ini ketika menyatakan:
“Manusia bukanlah tuan atas makhluk-makhluk. Manusia adalah gembala dari Keberadaan” (Letter on Humanism, 2023).
Lebih lanjut, mengacu kepada visi ekologi yang tertanam dalam narasi teologis dan antaragama Indonesia—serta seperti yang tercermin dalam ungkapan oleh Kementerian Agama—argumen dari tulisan ini ingin menggarisbawahi bahwa ekoteologi tidak terbatas pada abstraksi teoretis. Sebaliknya, ia mewakili kerangka kerja eksistensial dan etis yang transformatif, mampu menjembatani kesadaran spiritual dan tanggung jawab ekologi dalam masyarakat pluralistik seperti yang ada di Indonesia (Nusantara). Manusia diciptakan sesuai dengan gambaran Tuhan (yaitu sebagai hamba/makhluk), manusia tidak diciptakan untuk menguasai bumi, tetapi untuk merawat bumi sebagaimana Tuhan telah melakukannya berulang-ulang.
Dengan demikian, kesadaran ekoteologi tidak mengangkat manusia ke posisi yang lebih tinggi, melainkan mengembalikannya ke asal-usulnya yang rendah hati: bergantung pada bumi, terbentuk dari tanah dan air yang hina, dan ditakdirkan untuk kembali kepada-Nya. Oleh karena itu, tujuan sejati ekoteologi bukanlah kepuasan diri melalui kemutakhiran atau hanya sebatas masturbasi intelektual, melainkan ini merupakan sebuah reformasi eksistensial—kembali kepada kerendahan hati, tanggung jawab, dan relasionalitas (ke sesama makhluk). Ini merupakan sebuah “movement” keterlibatan yang sebenar-benarnya, dengan ekoteologi menghancurkan ilusi supremasi manusia dan mengembalikan kemanusiaan pada identitas autentiknya sebagai bagian dari, bukan terpisah dari, penciptaan. Jauh dari sekadar merasakan kenikmatan dalam proses berpikir, ekoteologi, lebih jauh, mengajak pada pergeseran radikal dalam diri manusia: dari penakluk menjadi penjaga, dari makhluk yang terasing menjadi makhluk yang terintegrasi.
Oleh karena itu, dalam "movement" ekoteologi ini, manusia dapat belajar untuk melihat dirinya sebagai makhluk biasa, tanpa merasa lebih unggul dari ciptaan lain. Sikap rendah hati menjadi kunci utama. Justru melalui kerendahan hati itulah, manusia dapat menemukan kembali jati diri dan kemanusiaannya yang sejati.
References:
Heidegger, M. (2023). Letter on “Humanism”. Psyhology & society, (2), 51-74.